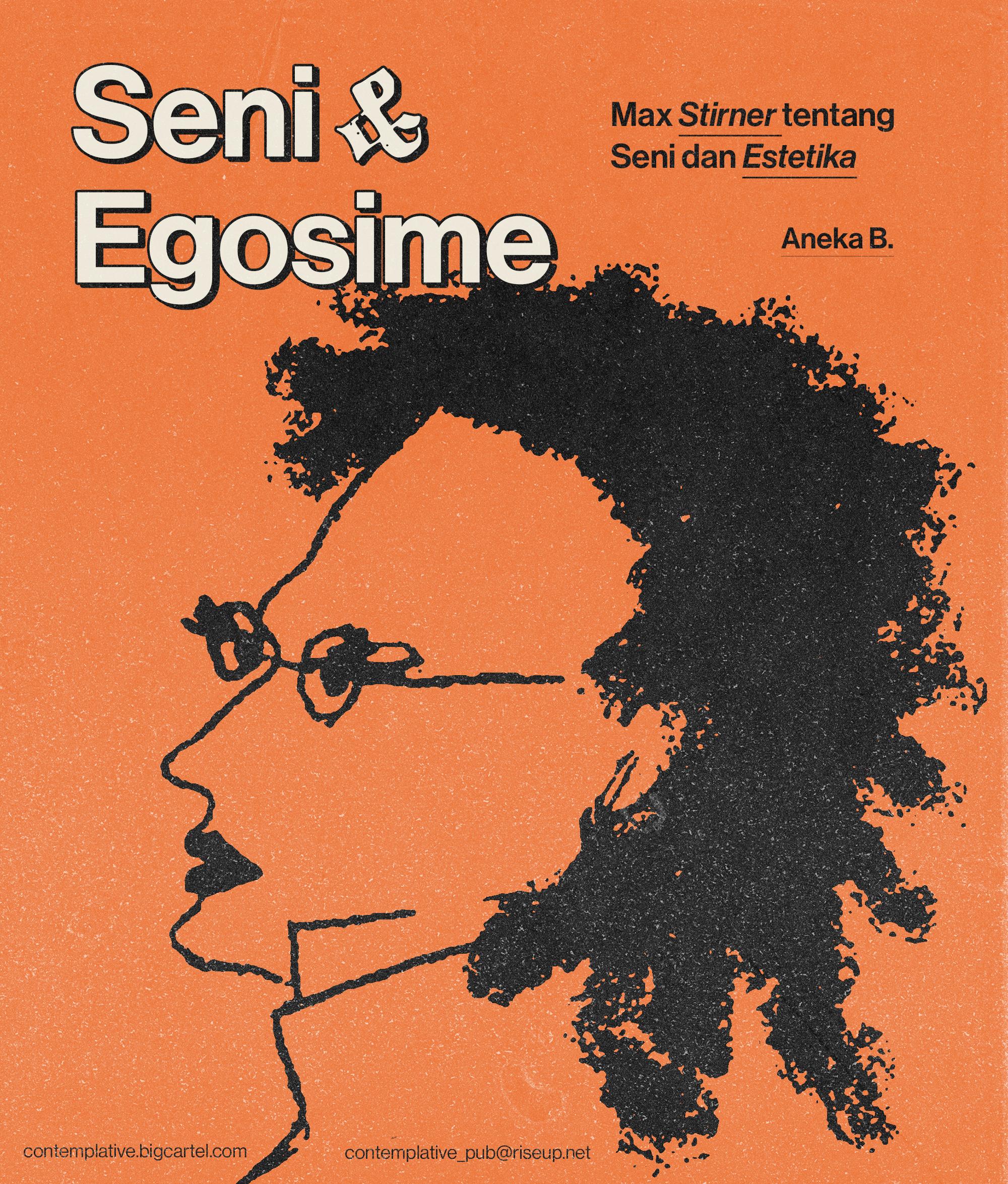
Seni dan Egoisme;
Max Stirner tentang Seni dan Estetika
Aneka B.
Max Stirner paling dikenal karena ide-ide radikalnya tentang individualitas dan egoisme, yang dituangkan dalam bukunya The Ego and Its Own (Der Einzige und sein Eigentum). Dalam buku ini, ia menjelaskan bahwa agensi dan realisasi diri berasal dari penolakan terhadap semua bentuk otoritas, baik otoritas eksternal seperti institusi maupun internalisasi seperti norma sosial. Teks ini mengeksplorasi pendekatannya yang unik dalam melepaskan diri dari otoritas dan internalisasi tersebut, untuk mencapai suatu bentuk ‘keberadaan diri’ yang ia sebut The Unique One (Der Einzige). Dengan cara ini, ia menantang legitimasi institusi, ideologi, dan pembentukan identitas yang muncul dari infiltrasi keinginan secara sadar atau tersembunyi, yang berfungsi sebagai kekuatan produktif dan aspek utama dalam pengalaman psikis individu.
Pandangan Stirner tentang seni, terutama yang diungkapkan dalam esainya Art and Religion (Kunst und Religion), menawarkan pengembangan yang menarik dari kerangka filosofisnya, meskipun esai ini diterbitkan sebelum karya utamanya.
Dalam esai ini, Stirner menghadirkan seni sebagai ekspresi egoisme—suatu usaha yang memungkinkan pengungkapan diri dan kenikmatan diri—serta sebagai pintu berbahaya menuju “spook-land” yang memiliki potensi untuk menjebak orang ke dalam perbudakan sensual.
Namun, dengan membandingkan seni dengan agama—yang ia kritik karena memaksakan ideal moral abstrak dan menyeluruh—Stirner berhasil menunjukkan bahwa potensi seni untuk ekspresi lebih kuat daripada potensi untuk dikooptasi. Ia menggambarkan seni sebagai area penciptaan bebas dalam dunia yang sensual, di mana individu dapat menegaskan otonomi dan kreativitas mereka.
Dengan menggali pandangan Stirner tentang seni, kita dapat memahami tema-tema filosofisnya yang lebih luas dan implikasinya terhadap estetika dan kreativitas dengan lebih mendalam. Dalam esai ini, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana seni dipersepsikan dan dikonseptualisasikan selama beberapa abad terakhir, lalu kita akan mengkaji lebih dekat bagaimana Max Stirner mengonseptualisasikan potensi seni yang unik dan jauh lebih maju melampaui zamannya.
Mendefinisikan Estetika
Untuk memahami potensi seni, kita perlu menyelami studi tentang Estetika, sebuah disiplin filosofis yang berkaitan dengan hakikat keindahan, seni, dan persepsi sensorik¾inderawi. Estetika mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat sesuatu indah, bagaimana seni diciptakan dan diinterpretasikan, serta peran pengalaman estetis dalam kehidupan dan budaya manusia.
Pada intinya, estetika mengkaji kualitas-kualitas yang membangkitkan emosi seperti empati, kesedihan, ketakutan, kecemasan, serta pengalaman sensorik seperti kenikmatan, kepuasan, atau rasa jijik, dan apa makna dari reaksi tersebut. Persepsi ini dapat mencakup sensasi visual (seni, desain), auditori (musik), taktil (tekstur), olfaktori (aroma), dan gustatori (rasa). Estetika juga mencakup studi tentang respons emosional dan intelektual terhadap rangsangan sensorik ini.
Bidang-bidang utama dalam estetika juga mencakup aspek sosial dan politik dari seni dan keindahan. Secara umum, estetika menyelidiki konsep keindahan dan dimensi subjektif serta objektifnya, mempertanyakan apakah keindahan bersifat universal atau ditentukan oleh budaya, serta bagaimana hal itu memengaruhi persepsi dan penilaian kita. Estetika juga menyoroti dampak psikologis dan emosional dari seni dan keindahan pada individu. Ini termasuk pembahasan tentang bagaimana pengalaman estetis membentuk identitas, empati, dan nilai-nilai budaya. Selain itu, estetika mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dalam konteks sosial dan politik, termasuk bagaimana seni dan keindahan berinteraksi dengan isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi.
Sejarah Singkat Estetika dalam Penyelidikan Filosofis
Immanuel Kant (1724-1804)
Kritik Kant terhadap Penilaian (Critique of Judgment) yang diterbitkan pada tahun 1790 sangat penting untuk memahami bagaimana ia melihat seni sebagai jembatan antara akal dan perasaan. Kant berpendapat bahwa penilaian estetis didasarkan pada perasaan subjektif daripada penalaran kognitif, menekankan sifat universal dan ketidakberpihakan dari apresiasi estetis. Ia menulis:
“Kecantikan adalah bentuk dari tujuan suatu objek, sejauh mana itu dirasakan tanpa adanya representasi tujuan.”
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
Kuliah Hegel tentang Estetika (1835) memberikan gambaran perkembangan sejarah seni sebagai manifestasi dari perkembangan roh dan kesadaran manusia. Ia melihat seni berkembang melalui berbagai tahap—simbolis, klasik, dan romantis—yang berpuncak pada roh absolut dalam filosofi. Hegel menyatakan:
“Seni, yang dipertimbangkan dalam panggilan tertingginya, adalah dan tetap bagi kita sesuatu yang berasal dari masa lalu.”
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Dalam The Birth of Tragedy (1872), Nietzsche membandingkan aspek Dionysian (emosional, kacau) dan Apollonian (rasional) dalam seni. Ia berargumen bahwa ketegangan antara kedua kekuatan ini melahirkan seni yang besar, terutama drama tragis, yang mengungkapkan kebenaran eksistensial yang mendalam. Nietzsche menulis:
“Tanpa musik, hidup akan menjadi sebuah kesalahan.”
Martin Heidegger (1889-1976)
Dalam The Origin of the Work of Art (1935), Heidegger membahas seni sebagai cara bagi manusia untuk mengungkap kebenaran tentang keberadaan dan eksistensi. Ia menekankan bahwa karya seni berfungsi sebagai “penempatan ke dalam karya” yang membuka dunia makna, menantang pandangan tradisional yang menganggap seni hanya sebagai representasi. Heidegger mencerminkan:
“Esensi dari karya seni adalah kebenaran yang menempatkan dirinya untuk bekerja.”
Theodor Adorno (1903-1969)
Dalam Aesthetic Theory (1970), Adorno mengeksplorasi hubungan antara seni dan masyarakat, khususnya dalam konteks modernitas dan kapitalisme. Ia mengkritik komodifikasi seni dan mendorong otonomi serta potensi kritisnya. Adorno berargumen:
“Seni adalah sihir yang dibebaskan dari kebohongan bahwa ia adalah kebenaran.”
Jacques Derrida (1930-2004)
Jacques Derrida, seorang tokoh penting dalam pemikiran poststrukturalis, menantang pengertian tradisional tentang seni dan estetika melalui konsep dekonstruksi. Ia mempertanyakan kestabilan makna dalam seni dan bahasa, menyarankan bahwa interpretasi bersifat dinamis dan tergantung pada konteks. Derrida menulis:
“Tidak ada yang berada di luar teks.”
Michel Foucault (1926-1984)
Eksplorasi Michel Foucault dalam The Order of Things (1966) dan karya-karya lainnya mengkaji bagaimana struktur kekuasaan membentuk pengetahuan dan wacana tentang seni. Ia menyelidiki bagaimana sistem pemikiran mengkategorikan dan mengontrol praktik artistik, mengungkap dinamika sosial dan politik yang mendasarinya. Foucault menyatakan:
“Dalam masyarakat seperti kita, ‘visual’ bukan sekadar apa yang dapat dilihat atau bahkan apa yang terlihat; ia adalah suatu bidang pengetahuan dan kekuasaan.”
Susan Sontag (1933-2004)
Dalam Against Interpretation (1966) dan esai-esai lainnya, Susan Sontag menantang kecenderungan untuk menginterpretasikan seni hanya melalui analisis kritis. Ia mendorong untuk mengalami seni secara langsung dan merangkul dampak sensorik serta emosionalnya, alih-alih mereduksinya menjadi wacana intelektual. Sontag secara provokatif menyatakan:
“Interpretasi menganggap pengalaman sensorik dari karya seni sebagai hal yang sudah pasti, dan melanjutkan dari sana.”
Pemikiran Max Stirner tentang seni terhubung dengan berbagai teori yang disajikan di sini dengan cara yang unik. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Max Stirner mengonseptualisasikan estetika dan seni.
Seni sebagai Egoisme
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Max Stirner mengonseptualisasikan seni dalam dua cara yang berlawanan. Di satu sisi, seni dipandang sebagai bentuk egoisme, sementara di sisi lain, seni dianggap berpotensi berbahaya bagi integritas individu karena kemampuannya mempengaruhi individu secara emosional dan sensorik. Mari kita terlebih dahulu melihat ‘cara positif’ yang secara tidak langsung diterapkan Stirner pada seni dalam teks-teksnya, The Ego and Its Own dan Art & Religion.
Seni sebagai Ekspresi Diri dan Agensi
Filsafat Max Stirner menempatkan penekanan yang signifikan pada individualitas dan ekspresi diri, yang dapat langsung dihubungkan dengan seni sebagai bentuk ekspresi diri. Meskipun Stirner tidak banyak menulis tentang seni, gagasannya tentang egoisme dan penegasan diri memberikan dasar yang kaya untuk memahami seni dalam konteks ini. Dalam kutipannya dari The Ego and Its Own, ia menyatakan:
“Aku adalah milikku sendiri hanya ketika aku menguasai diriku sendiri, alih-alih dikuasai oleh sensualitas atau oleh hal lainnya (Tuhan, manusia, otoritas, hukum, negara, gereja, dll.); yang berguna bagi diriku bukanlah yang baik pada dirinya sendiri, tetapi yang baik diriku sendiri.”
— Max Stirner, The Ego and Its Own
Kutipan ini menyoroti keyakinan Stirner akan penguasaan diri sebagai jalan menuju agensi dan pentingnya otonomi. Jika diterapkan pada seni, ini menunjukkan bahwa ekspresi artistik bukan tentang mengikuti standar atau ideal, tetapi tentang apa yang benar-benar mencerminkan dan melayani ego yang mengalami.
Seni sebagai ekspresi diri berfokus pada penyampaian keaslian sang artis, yang—bagi Stirner—adalah apa pun yang ingin diungkapkan oleh artis tersebut. Dengan demikian, seni merupakan pernyataan langsung tentang keunikan seseorang, kecuali jika karya tersebut dibuat untuk tujuan lain, dalam hal ini bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan atau hal-hal lainnya. Dalam kerangka egois, ini sepenuhnya sah asalkan tidak berasal dari keinginan untuk mendapatkan persetujuan sosial.
Seperti yang disebutkan dalam paragraf di atas, seni dapat dianggap sebagai ekspresi kepemilikan diri. Dan kepemilikan diri mengimplikasikan agensi. Dengan menciptakan seni sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang melayani keinginan pribadi, seni tersebut menjadi ekspresi dari agensi. Artis mengendalikan narasi pribadi dan keberadaan mereka, serta memperkuat penguasaan atas identitas mereka sendiri.
Seni sebagai Keintiman dengan Diri Sendiri
“Manusia adalah makhluk tertinggi bagi sesamanya, dan fakta ini tidak bergantung pada individualitas masing-masing.”
— Max Stirner, The Ego and Its Own
Stirner melihat seni sebagai bentuk kedekatan atau koneksi dengan diri sendiri. Ini merupakan bentuk dasar dari kepuasan diri dan pengungkapan diri yang menonjolkan nilai pribadi dan intrinsik dari penciptaan artistik.
Kutipan ini menekankan keyakinan Stirner akan pentingnya individu dan kekuatan kreatif yang melekat pada setiap orang. Ini menunjukkan bahwa penciptaan artistik adalah aspek mendasar dalam mengekspresikan individualitas seseorang serta menegaskan kehendak dan kemampuan unik yang dimiliki.
“Karena seni telah menciptakan Ideal bagi manusia, dan dengan ini memberikan objek bagi pemahaman manusia untuk dipertaruhkan, sebuah pertandingan yang pada akhirnya akan memberikan nilai pada objek-objek kosong dari pemahaman tersebut, maka seni adalah pencipta agama…”
— Max Stirner, Art & Religion
Melalui seni, individu dapat mengekspresikan perspektif, emosi, dan ide yang khas, serta terhubung dengan kreativitas pribadi mereka dengan cara yang unik.
Seni sebagai Pembebasan
“Seni tidak akan membebaskan dirinya dari gereja dan negara sampai ia membebaskan dirinya dari dirinya sendiri.”
— Max Stirner, The Ego and Its Own
Kutipan ini menangkap visi Stirner tentang pembebasan sebagai proses melepaskan diri dari batasan realitas untuk terlibat dalam penciptaan tanpa batas dari dunia sendiri. Jika diterapkan pada seni, ini menunjukkan bahwa seni dapat berfungsi sebagai sarana pembebasan, untuk melampaui batasan sosial dan mengeksplorasi kebebasan kreatif.
Dengan cara ini, seni menyediakan cara untuk melampaui batasan yang diberlakukan oleh masyarakat, budaya, dan realitas. Seni sebagai bentuk pembebasan melibatkan kebebasan untuk mencipta dan menghancurkan tanpa batasan, serta menggugat paradigma yang ada dan mengeksplorasi kemungkinan baru dalam cara apa pun yang dipilih individu.
Seni sebagai Kritik Sosial
“Para atheis kita adalah orang-orang yang saleh. Memang, mereka tidak lagi percaya pada Tuhan pribadi, tetapi mereka masih percaya pada ‘esensi yang lebih tinggi,’ yaitu Manusia, Kemanusiaan. Esensi manusia adalah phantasm yang sama seperti esensi Tuhan: ia adalah hantu.”
— Max Stirner, The Ego and Its Own
Kutipan ini menggambarkan kritik Stirner terhadap ideal dan konstruksi sosial, yang ia anggap sebagai spooks atau ilusi abstrak yang memiliki kekuatan atas individu. Jika diterapkan pada seni, Stirner kemungkinan akan mendukung ide seni yang mengkritik konstruksi sosial ini—baik yang bersifat religius, politik, maupun budaya—dengan mengungkapnya sebagai ilusi belaka yang membatasi kepemilikan diri.
Seni yang menantang ideal “Manusia” dan “Kemanusiaan” sebagai esensi yang lebih tinggi kemungkinan besar akan disetujui oleh Stirner, karena dapat membongkar mesin produksi makna yang besar dan mengungkapkan sifatnya yang menindas dengan cara yang dapat dipahami dan diakses.
Meskipun Stirner tidak secara eksplisit membahas seni sebagai bentuk kritik sosial, posisi filosofisnya terhadap konstruksi sosial memberikan dasar yang kuat untuk menginterpretasikan seni dalam konteks ini. Seni yang menantang norma-norma sosial, mengungkap ilusi, dan mempromosikan kepemilikan diri individu dapat dilihat sebagai perpanjangan dari kritik Stirner terhadap ideal sosial dan egoismenya.
Seni sebagai Penolakan terhadap Otoritas Makna
“Kebiasaan bahasa telah melatih kita untuk memisahkan hal-hal di mana tidak ada pemisahan yang seharusnya, dan untuk menciptakan kategori di mana hanya ada operasi, aktivitas. Kebiasaan bahasa melihat dalam tindakan, pekerjaan, dan sebagainya, sesuatu yang berbeda dari tindakan itu sendiri; ia membedakan antara produsen dan produk, pelaku dan tindakan. Pelaku bukanlah segalanya dalam tindakan, produk, tetapi ia terlibat dalam setiap aspek dari aksi tersebut.”
— Max Stirner, The Ego and Its Own
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Stirner melihat seni sebagai kekuatan destruktif yang dapat membantu individu dalam mencapai realisasi diri. Kutipan di atas mencerminkan kritik lebih luas Stirner terhadap konsep abstrak dan norma universal. Jika diterapkan pada seni, Stirner kemungkinan akan memandang konvensi artistik dan gagasan tentang keindahan universal sebagai konstruksi buatan yang memberlakukan standar pada ekspresi individu.
Intinya, Stirner kemungkinan akan menolak gagasan tentang keindahan universal demi pendekatan estetika yang lebih subjektif dan individualistik, di mana keindahan didefinisikan oleh diri sendiri dan pengalaman serta ekspresi uniknya.
Potensi Gelap Seni
Max Stirner menyajikan perspektif unik tentang estetika dalam esainya Art and Religion (bersamaan dengan karya utamanya) yang menawarkan pandangan menyeluruh tentang seni. Ia juga mengarahkan perhatian pada potensi seni dengan cara yang tidak akan muncul kembali hingga beberapa waktu kemudian, sehingga dalam hal ini, ia jelas merupakan pemikir yang lebih maju pada masanya.
Menentang Ideal Romantis
Bagi para pemikir seperti Kant, Hegel, serta Nietzsche dan Heidegger, seni mencerminkan ideal-ideal keindahan, kebenaran, dan nilai-nilai spiritual atau budaya yang lebih tinggi. Mereka mengeksplorasi potensi transformatif dan mengangkat seni, kemampuannya untuk mengungkapkan kebenaran tentang keberadaan, serta perannya dalam perkembangan spiritual dan budaya. Para filsuf ini merayakan alam, melihat ekspresi individu sebagai sesuatu yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada individu itu sendiri, dan mereka mencari serta membayangkan kedalaman emosional yang terkandung dalam seni. Mereka menganggap seni sebagai sarana untuk berinteraksi dengan aspek-aspek yang sublim dan irasional dari pengalaman manusia.
“Hegel membahas seni sebelum agama. Urutan ini memang tepat, bahkan hanya dari sudut pandang sejarah. Ketika manusia mulai merasa bahwa ada sisi lain dari dirinya (Jenseits) yang terpendam, dan bahwa keadaan alami semata tidaklah cukup, ia akan terdorong untuk membagi dirinya antara apa yang sebenarnya ia adalah dan apa yang seharusnya ia capai.”
— Max Stirner, Art and Religion
Terkait dengan Hegel, misalnya, Stirner merasa bahwa jenis konseptualisasi yang menghilangkan peran individu itu sulit diterima. Ia mengkritik gagasan romantis tentang seni yang mengangkatnya ke ranah transendental atau ideal di luar pengalaman individu. Stirner berargumen bahwa seni dapat menjadi alat dominasi dan ilusi, digunakan oleh otoritas (baik itu religius, budaya, atau politik) untuk memaksakan ideologi dan memanipulasi individu. Ia melihat seni sebagai potensi untuk memperkuat norma-norma sosial dan struktur kekuasaan, bukannya membebaskan individu dari mereka. Ia menolak gagasan bahwa seni harus berfungsi sebagai kendaraan untuk kebenaran budaya, sosial, atau religius, dan bahwa seni seharusnya tidak melebihi ranah melayani keinginan dan kepentingan individu.
Ketika membahas kehidupan secara umum, fokus Stirner adalah pada saat ini yang dialami oleh individu, dengan penekanan yang mendalam pada pentingnya otonomi dan kepentingan diri. Ia menekankan bahwa individu harus selalu menyadari nilai dari pengalaman mereka sendiri, tanpa melupakan esensi kebebasan dan hak untuk mengutamakan diri sendiri dalam setiap aspek kehidupan.
Konsep here-and-now juga terdapat dalam karya Heidegger. Ia menyebutnya Dasein, yang pada dasarnya merupakan cara elegan untuk mengatakan bahwa eksistensi manusia memiliki keistimewaan karena dialami oleh individu. Filsafat Heidegger, terutama dalam The Origin of the Work of Art, mengeksplorasi seni sebagai proses yang mengungkapkan kebenaran dan makna dari eksistensi manusia. Heidegger melihat seni sebagai cara bagi manusia untuk menghadapi dan memahami eksistensi mereka dengan lebih otentik, melampaui rasionalitas semata. Ia menekankan peran seni dalam mengungkap dunia dan mengungkapkan kebenaran ontologis yang lebih dalam tentang keberadaan di dunia.
Kritik Stirner terhadap romantisme dalam seni, terutama terkait potensinya untuk menciptakan ilusi dan patung-patung palsu, secara tidak langsung menantang penekanan Heidegger pada kapasitas revelatori seni. Stirner menolak gagasan bahwa seni harus berfungsi sebagai sarana untuk kebenaran transendental atau nilai-nilai sosial. Bagi Stirner, individu tidak perlu menjadi bagian dari pengalaman yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Ia menekankan bahwa seni seharusnya berfokus pada ekspresi dan keinginan individu, bukan pada penggambaran ideal-ideal yang mungkin menyesatkan atau mengekang kebebasan pribadi.
“Seni menciptakan perpecahan, karena ia menempatkan Ideal di atas dan melawan manusia. Namun pandangan ini, yang telah lama bertahan, disebut agama, dan itu hanya akan bertahan sampai sebuah mata yang menuntut kembali menarik Ideal tersebut ke dalam diri dan menelannya.”
— Max Stirner, Art & Religion
Estetika Praktis
Berbeda dengan Kant, Hegel, Nietzsche, dan bahkan Heidegger yang membahas estetika dalam dimensi teoritis dan filosofis, pendekatan Stirner terhadap estetika lebih pragmatis. Ia menekankan kegunaan praktis seni dalam memenuhi keinginan dan kepentingan individu. Stirner melihat seni sebagai sarana ekspresi pribadi dan menikmati hidup, bukan sebagai objek kontemplasi intelektual atau validasi budaya. Ia peduli dengan bagaimana individu dapat menggunakan seni untuk menegaskan keunikan diri mereka dan sebagai cara untuk menantang norma dan ideologi yang berlaku.
Penekanan Stirner pada kegunaan praktis seni sejalan dengan kritik Sontag terhadap kecenderungan mengintellectualisasi seni dalam Against Interpretation (1966). Sontag menentang pengurangan seni menjadi sekadar teori atau interpretasi, dan sebaliknya mendorong keterlibatan langsung yang bersifat sensoris dengan karya seni. Pandangan ini selaras dengan sudut pandang Stirner yang melihat seni sebagai sarana ekspresi pribadi dan menikmati hidup, yang melayani keinginan dan kepentingan individu, bukan ideal-ideal abstrak atau kontemplasi filosofis.
“Seni menciptakan perpecahan, karena ia menempatkan Ideal di atas dan melawan manusia. Namun pandangan ini, yang telah lama bertahan, disebut agama, dan itu hanya akan bertahan sampai sebuah mata yang menuntut kembali menarik Ideal tersebut ke dalam diri dan menelannya.”
— Max Stirner, Art & Religion
Selain itu, Stirner dan Sontag berbagi keprihatinan terhadap otonomi dan keunikan pengalaman individu dalam hubungan dengan seni. Konsep keunikan (Eigenheit) yang diajukan Stirner menekankan pentingnya individu untuk menegaskan identitas dan keinginan unik mereka melalui seni, yang pada dasarnya merupakan bentuk legitimasi diri dan penolakan terhadap norma-norma dan ideologi masyarakat. Demikian pula, Sontag menekankan peran seni dalam memperluas kesadaran individu dan melawan batasan-batasan dari kerangka budaya dan intelektual yang berusaha membatasi atau mendefinisikan ekspresi artistik.
Kepemilikan dan Seni
Stirner juga menolak gagasan bahwa seni memiliki nilai budaya atau sosial. Ini dapat dilihat sebagai perpanjangan dari pandangannya yang radikal tentang kepemilikan, yang menantang konsepsi konvensional tentang properti dan kepemilikan. Ia menolak ide bahwa apa pun yang diciptakan oleh keunikan individu seharusnya atau dapat dimiliki atau dikendalikan oleh otoritas, baik itu lembaga budaya, pemerintah, atau norma-norma masyarakat. Bagi Stirner, seni seharusnya menjadi ekspresi bebas dari individu, tanpa intervensi atau pengendalian dari kekuatan eksternal, sehingga memungkinkan individu untuk menegaskan identitas dan keinginan mereka secara otentik.
“Seni menciptakan Objek, dan agama hanya hidup dalam banyak keterikatannya pada Objek itu, tetapi filsafat dengan jelas memisahkan dirinya dari keduanya. Filsafat tidak terjerat dengan sebuah Objek, seperti agama, dan tidak menciptakannya, seperti seni, melainkan meletakkan tangannya yang menghancurkan pada seluruh urusan penciptaan Objek dan keseluruhan objektivitas itu sendiri, sehingga ia menghirup udara kebebasan.”
— Max Stirner, Art & Religion
Penolakan Stirner terhadap nilai budaya atau sosial seni sejajar dengan eksplorasi Foucault tentang bagaimana pengetahuan dan praktik budaya dibentuk oleh dinamika kekuasaan. Dalam karya-karyanya, seperti The Order of Things dan Discipline and Punish, Foucault mengkritik bagaimana lembaga dan wacana membangun serta menegakkan norma dan nilai. Demikian pula, Stirner berargumen menentang penetapan nilai-nilai budaya atau sosial pada seni, menekankan bahwa seni seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan dan norma yang membatasi ekspresi individu. Dengan cara ini, keduanya mendorong pemikiran kritis terhadap bagaimana seni dan pengetahuan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan mendorong otonomi individu dalam penciptaan dan interpretasi.
Seni dan Komodifikasi
Berbeda dengan Hegel, Kant, Heidegger, dan Nietzsche, Stirner mengkritik komodifikasi seni sebagai bentuk alienasi dan dominasi. Ia skeptis terhadap bagaimana seni dapat diambil alih dan digunakan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi individu. Fokus Stirner adalah pada menjaga keaslian dan makna pribadi seni.
Kritik terhadap komodifikasi seni ini sejalan dengan perspektif Michel Foucault dan Theodor Adorno, meskipun dari sudut pandang yang berbeda dalam ranah kritik budaya dan filosofis.
“Seni, selain filsafat, terpaksa menarik keluar dari ketersembunyiannya dalam kegelapan yang menyembunyikan subjek bentuk yang paling tepat dan terbaik dari roh, serta ekspresi roh yang paling diidealkan, dan mengembangkannya untuk dilepaskan sebagai sebuah Objek. Dalam konteks ini, manusia berdiri di hadapan Objek ini, ciptaan dari rohnya, seperti di hadapan Tuhan, dan bahkan sang seniman pun merendahkan diri di hadapannya.”
— Max Stirner, Art & Religion
Analisis Foucault tentang relasi kekuasaan dalam Discipline and Punish dan karya-karya lainnya memberikan kerangka untuk memahami kekhawatiran Stirner tentang komersialisasi seni. Foucault mengamati bagaimana institusi dan wacana mengendalikan artefak budaya, termasuk seni, serta menentukan nilainya dalam masyarakat. Ia mengkritik cara-cara di mana kekuatan ekonomi dan struktur kekuasaan mengatur produksi dan konsumsi seni, karena hal ini memiliki pengaruh besar terhadap seni apa yang diciptakan, dipamerkan, dan dihormati.
“Metode pelatihan yang nyata dan terus-menerus, latihan yang ketat dan tidak terputus, dipaksakan oleh metode pemaksaan arsitektural ini. Pemaksaan yang konstan yang dikenakan kepada individu oleh sebuah korporasi, yang dibentuk oleh individu-individu yang bersatu untuk menyusunnya.”
¾Michel Foucault, Discipline and Punish.
Adorno, anggota terkemuka dari Sekolah Frankfurt, membahas komodifikasi seni secara mendalam dalam karyanya Aesthetic Theory dan tulisan-tulisan lainnya. Ia mengkritik bagaimana masyarakat kapitalis mengubah seni menjadi komoditas, menghilangkan potensi kritis dan radikalnya. Adorno berargumen bahwa otonomi dan keaslian seni terancam ketika seni terpengaruh oleh kekuatan pasar dan kepentingan komersial. Ia melihat komodifikasi sebagai bentuk alienasi yang mendistorsi kemampuan seni untuk menantang ideologi dominan dan menawarkan pengalaman estetis yang sejati.
“Seluruh dunia dibuat untuk melewati saringan industri budaya. Pengalaman lama penonton film, yang melihat dunia di luar sebagai perpanjangan dari film yang baru saja ditontonnya (karena film tersebut berusaha mereproduksi dunia persepsi sehari-hari), kini menjadi pedoman produsen. Semakin intens dan sempurna tekniknya menggandakan objek empiris, semakin mudah hari ini untuk menciptakan ilusi bahwa dunia luar adalah kelanjutan langsung dari apa yang ditampilkan di layar. Tujuan ini juga melayani seni lukis modern, baik itu puris maupun abstrak.”
¾Theodor W. Adorno, The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception, dalam Dialectic of Enlightenment (ditulis bersama Max Horkheimer)
Skeptisisme Stirner terhadap idealisasi seni mencerminkan kritik mereka terhadap bagaimana sistem kapitalis dan kerangka institusional memanipulasi serta mengeksploitasi produk budaya untuk keuntungan ekonomi atau kontrol sosial. Fokus Stirner pada pelestarian makna pengalaman pribadi yang bersifat sementara dalam seni dan ekspresi artistik menantang pengaruh mendalam dari tekanan idealistis dan ekspektasi masyarakat.
Mengapa Sisi Gelap Tak Akan Pernah Menang
Stirner menunjukkan kepada kita kedua sisi seni dan estetika. Ia menjelaskan bahwa seni adalah pengalaman yang menyenangkan bagi individu, dalam cara apa pun yang mereka sukai, atau, bisa jadi diserap dan digunakan untuk menjebak kita dalam dunia ilusi. Ini tidak dilakukan melalui proses atau rencana yang dipikirkan dengan matang oleh otoritas tertentu. Ini dilakukan melalui idealisme—artinya, melalui keyakinan pada suatu esensi fundamental yang melampaui kesenangan sesaat dan pengalaman diri atau keterhubungan diri individu. Inilah sebabnya ia membandingkannya dengan iman religius.
Perbandingan langsungnya membantu kita memahami potensi negatif dan positif dari seni dalam kerangka egois.
Inspirasi Artistik dan Iman Religius
Inti dari perspektif Stirner adalah perbedaan antara inspirasi artistik dan iman religius, yang menurutnya secara fundamental membentuk dampak keduanya terhadap individu dan masyarakat.
Stirner menarik paralel antara seni dan agama, menunjukkan bahwa keduanya melibatkan bentuk antusiasme yang mengangkat individu. Namun, ia juga membedakan antara keduanya, mencatat bahwa sementara inspirasi artistik terkait dengan kreativitas, iman religius terkait dengan kepercayaan pada sesuatu di luar diri.
Jadi, meskipun ia mengakui bahwa keduanya melibatkan bentuk antusiasme yang mengangkat individu dari keberadaan yang sehari-hari, ia juga menyoroti perbedaan penting: inspirasi artistik berakar pada kreativitas dan kapasitas ekspresif individu, sementara iman religius bergantung pada kepercayaan pada sesuatu di luar diri—sebuah doktrin atau dewa eksternal.
Esensi Seni dan Agama
Stirner lebih menjelaskan pandangannya dengan mencatat bahwa keduanya mampu menghadirkan ideal yang lebih tinggi yang melampaui eksistensi manusia. Namun, dia menekankan bahwa mereka melakukannya dengan cara yang berbeda.
Seni, menurut Stirner, menciptakan dunia yang sensual—sebuah ranah yang nyata dan sensorik yang mencerminkan ekspresi imajinatif si pencipta. Sebaliknya, agama membangun dunia intelektual atau suprasensual—sebuah ranah abstrak dari kepercayaan dan ideal yang melampaui pengalaman sensorik yang langsung.
Pembedaan ini menegaskan pandangan Stirner bahwa seni beroperasi dalam ranah kreativitas pribadi dan persepsi sensorik, menawarkan ruang bagi individu untuk menjelajahi dan mengekspresikan perspektif unik mereka tanpa paksaan dari dogma atau otoritas eksternal.
Kebebasan dan Batasan dalam Seni
Stirner mengakui bahwa seni memungkinkan adanya kebebasan berekspresi dalam dunia sensorik. Dia berpendapat bahwa meskipun seni membebaskan jiwa untuk mencipta dan berinovasi, seni tetap terikat oleh batasan-batasan duniawi. Perspektif yang mendalam ini mencerminkan pengakuan Stirner bahwa seni, meskipun menawarkan kebebasan dan kreativitas, masih dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan keterbatasan praktis.
Namun, meskipun ada batasan-batasan ini, Stirner menghargai seni sebagai ranah penciptaan yang bebas dalam dunia sensorik. Dia melihat kebebasan ini sebagai hal yang esensial bagi individu untuk menegaskan otonomi mereka dan menantang ekspektasi konvensional.
Akhirnya, perspektif Stirner tentang seni merayakan kapasitasnya untuk menginspirasi dan mengangkat individu, serta memperingatkan tentang bahaya penetapan ideologis dan religius.
Namun, ini adalah garis yang sangat tipis. Jadi, ingatlah untuk tidak membiarkan “spooks” menguasaimu.
Daftar Pustaka
Buku karya Max Stirner:
- Stirner, Max. The Ego and Its Own (Der Einzige und sein Eigentum).
Free Link: The Ego and Its Own - Stirner, Max. Art and Religion (Kunst und Religion).
Free Link: Art and Religion
Buku tentang Estetika dan Filsafat:
- Kant, Immanuel. Critique of Judgment. 1790.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Lectures on Aesthetics. 1835.
- Nietzsche, Friedrich. The Birth of Tragedy. 1872.
- Heidegger, Martin. The Origin of the Work of Art. 1935.
- Adorno, Theodor. Aesthetic Theory. 1970.
- Adorno, Theodor. The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception, in Dialectic of Enlightenment (co-authored with Max Horkheimer).
- Derrida, Jacques. Of Grammatology. 1967. (Relevant to his concept of deconstruction.)
- Foucault, Michel. The Order of Things. 1966.
- Foucault, Michel. Discipline and Punish. 1975.
- Sontag, Susan. Against Interpretation. 1966.
